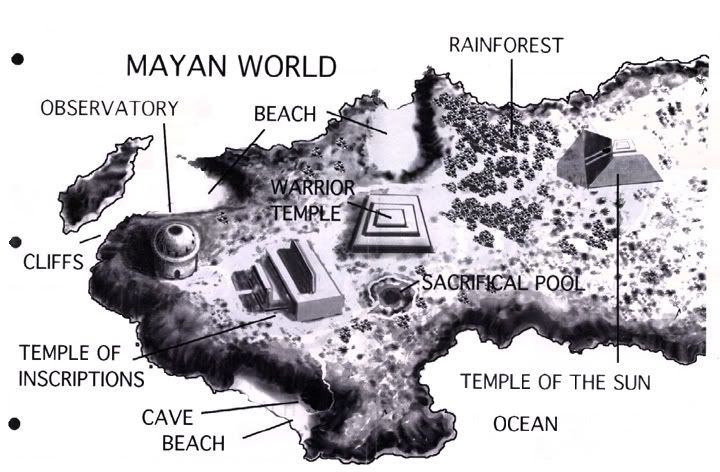Setelah menunggu empat dekade, akhirnya terbitlah buku yang menguak misteri peristiwa Gerakan 30 September. Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, terjemahan dari buku Pretext for Mass Murder karya John Roosa.
Oleh Asvi Warman Adam, ahli peneliti utama LIPI; dikutip Blog Berita dari Koran Tempo edisi 28 April 2008Ketidakjelasan itu bertahan demikian lama karena rezim Orde Baru melakukan monopoli sejarah dan memupuknya bertahun-tahun. Versi lain, seperti yang ditulis oleh Ben Anderson dan kawan-kawan (kemudian dikenal sebagai Cornell Paper), yang menganggap bahwa itu persoalan intern AD (Angkatan Darat), dilarang dan penulisnya dicekal masuk Indonesia. Perdebatan tentang Gerakan 30 September diharamkan, bahkan usaha ISAI (Institut Studi Arus Informasi) menerbitkan buku tipis tentang masing-masing versi Gerakan 30 September itu diganjal Kejaksaan Agung pada tahun 1995.
Dalam suasana demikian, ketika Soeharto jatuh, bermunculanlah di tanah air berbagai (terjemahan) tulisan tentang Gerakan 30 September sejak tahun 1998. Analisis yang diberikan beragam, mulai dari kudeta merangkak (Saskia Wieringa, Peter Dale Scott, Subandrio) sampai dengan kudeta yang disengaja untuk gagal seperti yang ditulis Coen Hotzappel.
Memang ada berbagai kelompok yang diuntungkan dengan kegagalan kudeta itu, namun apakah pihak tersebut mendesain peristiwa itu sedemikian rupa dengan skenario yang rapi dan semuanya berjalan seperti yang diharapkan mereka? Tampaknya tidak demikian.
Namun, masing-masing teori itu memiliki kelemahan. Kalau disebutkan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) secara keseluruhan melakukan pemberontakan, kenapa 3 juta anggota partai ini tidak melakukan perlawanan ketika diburu dan dibunuh setelah gerakan itu meletus? Kenapa partai komunis terbesar ketiga di dunia saat itu begitu mudah dirontokkan?
Analisis yang menyebutkan bahwa itu persoalan intern Angkatan Darat juga tidak memuaskan karena persoalannya tidak sesederhana itu. Bukankah Sjam dan Pono juga terlibat? Sementara itu, versi Soekarno sebagai dalang juga diragukan. Bila sang presiden mengetahui sepenuhnya rencana aksi ini sebelumnya, kenapa ia berputar-putar di kota Jakarta sebelum menuju pangkalan udara tanggal 1 Oktober 1965? Mengapa Presiden Soekarno tidak langsung saja dari Wisma Yaso kediaman Ratna Sari Dewi (sekarang Museum Satria Mandala di Jalan Gatot Subroto) menuju Halim Perdanakusuma?
Demikian pula Soeharto tidaklah terlampau “jenius” untuk bisa merancang suatu perebutan kekuasaan secara sistematis. Masih perlu diinvestigasi lebih lanjut seberapa jauh Soeharto mengetahui rencana tersebut sebagaimana disampaikan Kolonel Latif dalam pertemuan malam sebelumnya di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto.
Amerika Serikat (AS) tidaklah ikut campur pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965, walaupun berbagai dokumen menyebut keterlibatan mereka sebelum dan sesudah peristiwa berdarah tersebut. Bagi pemerintah AS waktu itu, bila Indonesia dengan penduduk keempat atau kelima terbesar di dunia itu–dengan sumber daya alam berlimpah dan posisi sangat strategis– jatuh ke tangan komunis, berarti telah terjadi kiamat.
Judul buku: Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto
Pengarang: John Roosa
Penerjemah: Hersri Setiawan
Penerbit: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra
Tebal: 392 halaman
Riset yang dilakukan John Roosa menggunakan arsip yang jarang diulas secara utuh selama ini, seperti dokumen Supardjo, tulisan-tulisan Muhammad Munir dan Iskandar Subekti yang tersimpan di Amsterdam, wawancara dengan tokoh-tokoh PKI seperti “Hasan” yang meminta dirahasiakan identitasnya sampai ia meninggal.
Muhammad Munir adalah anggota Politbiro PKI dan Iskandar Subekti adalah panitera Politbiro PKI, yang pada tanggal 1 Oktober 1965 mengetik pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan Gerakan 30 September. Adapun “Hasan” memiliki posisi yang dianggap logis mengetahui kegiatan Biro Chusus. “Hasan” sendiri sudah menulis memoar yang sudah diserahkan kepada penulis buku (John Roosa) yang dapat dipublikasikan setelah ia meninggal. Di samping dokumen-dokumen penting itu, serta wawancara mendalam dengan tokoh sentral organisasi kiri itu, arsip-arsip yang berasal dari Departemen Luar Negeri AS membantu menjelaskan berbagai hal.
Dokumen Supardjo dianggap cukup sahih–sebagai semacam pertanggungjawaban setelah peristiwa itu terjadi–yang ditulis ketika ia belum tertangkap. Beberapa saksi, termasuk Letnan Kolonel Udara Heru Atmodjo, yang sama-sama di penjara dengan Supardjo, mengakui keberadaan surat tersebut. Pihak keluarga juga mengiyakan informasi yang pernah disampaikan Supardjo.
Dokumen itu memperlihatkan bahwa kelemahan utama Gerakan 30 September adalah karena tidak adanya satu komando. Terdapat dua kelompok pimpinan, yakni kalangan militer (Untung, Latief dan Sudjono) dan pihak Biro Chusus PKI (Sjam, Pono, Bono dengan Aidit di latar belakang). Sjam memegang peran sentral karena ia berada dalam posisi penghubung antara kedua pihak ini.
Namun, ketika upaya ini tidak mendapat dukungan dari Presiden Soekarno, bahkan diminta untuk dihentikan, maka kebingungan terjadi dan kedua kelompok ini pecah. Kalangan militer ingin mematuhi permintaan Soekarno, sedangkan Biro Chusus tetap melanjutkannya. Ini dapat menjelaskan mengapa antara pengumuman pertama dengan kedua dan ketiga terdapat selang waktu sampai lima jam. Sesuatu yang dalam upaya kudeta merupakan kesalahan besar. Pada pagi hari mereka mengumumkan bahwa Presiden dalam keadaan selamat. Sedangkan pengumuman berikutnya pada siang hari sudah berubah drastis (pembentukan Dewan Revolusi dan pembubaran kabinet).
Buku ini menyederhanakan kerumitan misteri itu dengan metode ala detektif. Pembaca diyakinkan bahwa tokoh kunci Gerakan 30 September, Sjam Kamaruzzaman, bukanlah agen ganda, apalagi triple agent, melainkan pembantu setia Aidit sejak bertahun-tahun. Pelaksana Biro Chusus PKI yang ditangkap tahun 1968 ini baru dieksekusi tahun 1986. Ia bagaikan putri Syahrazad yang menunda pembunuhan dirinya dengan menceritakan kepada raja sebuah kisah setiap malam, sehingga mampu bertahan selama 1001 malam. Sjam bertahan lebih dari 18 tahun dengan mengarang 1001 pengakuan.
Dokumen Supardjo mengungkapkan mengapa gerakan itu gagal dan tidak bisa diselamatkan. Kerancuan antara “penyelamatan Presiden Soekarno” dan “percobaan kudeta” dengan membubarkan kabinet dijelaskan dengan gamblang. Jauh sebelum peristiwa berdarah itu, AS telah memikirkan dan mendiskusikan segala tindakan yang perlu untuk mendorong PKI melakukan gebrakan lebih dahulu, sehingga dapat dipukul secara telak oleh Angkatan Darat. Dan, Aidit pun terjebak. Karena sudah mengetahui sebelum peristiwa itu terjadi, maka Soeharto adalah jenderal yang paling siap pada tanggal 1 Oktober 1965 ketika orang lain bingung dan panik. Nama Soeharto sendiri tidak dimasukkan dalam daftar perwira tinggi yang akan diculik.
Seperti disampaikan sejarawan Hilmar Farid dalam peluncuran buku ini di Yogyakarta, karya ini berjasa mengungkapkan bahwa Gerakan 30 September itu lebih tepat dianggap sebagai aksi (untuk menculik tujuh jenderal dan menghadapkan kepada Presiden), bukan sebagai gerakan. Karena peristiwa ini merupakan aksi sekelompok orang di Jakarta dan Jawa Tengah yang dapat diberantas dalam waktu satu-dua hari.
Namun, aksi ini (yang kemudian ternyata menyebabkan tewasnya enam jenderal) kemudian oleh Soeharto dan kawan-kawan dijadikan dalih untuk memberantas PKI sampai ke akar-akarnya, yang di lapangan menyebabkan terjadinya pembunuhan massal dengan korban lebih dari setengah juta jiwa. Kalau para jenderal yang diculik itu tertangkap hidup-hidup, mungkin sejarah Indonesia akan lain. Massa PKI akan turun ke jalan dan menuntut para jenderal itu dipecat. Presiden akan didesak untuk memberikan kursi departeman kepada golongan kiri itu, karena sampai tahun 1965 Soekarno tidak pernah mempercayakan pimpinan departemen kepada tokoh komunis kecuali Menteri Negara.
Buku ini memiliki kelemahan kecil, seperti penulisan Kapten Bambang Widjanarko (hal 116; seharusnya kolonel) dan Kolonel H Maulwi Saelan (hal 57; pada tahun 1965 Saelan belum naik haji). Saelan baru menunaikan rukun Islam itu pada era Orde Baru dan memimpin Yayasan Sekolah Islam Al Azhar.
Namun, di sisi lain, buku mempunyai banyak kelebihan. Pertama, menggunakan dokumen yang selama ini diabaikan, seperti dokumen Supardjo, pledoi Iskandar Subekti dan tulisan Muhammad Munir. Kedua, Roosa berhasil melakukan wawancara mendalam dengan “Hasan”, tokoh kunci yang mengetahui kiprah unit yang disebut sebagai Biro Chusus PKI.
Ketiga, sumber-sumber di atas dilengkapi dengan arsip-arsip Amerika Serikat yang telah terbuka dari waktu ke waktu dan menjadi perangkat yang andal untuk melakukan analisis sejarah. Keempat, John Roosa berhasil menyusun narasi baru bahwa Gerakan 30 September sebenarnya bukan gerakan, melainkan suatu aksi yang ternyata dijadikan dalih untuk melakukan pembunuhan massal.
Kelima, upaya yang sudah dilakukan dosen sejarah Universitas British Columbia, Kanada, ini menyebabkan perdebatan tentang siapa dalang G30S itu sudah sepatutnya diakhiri. Seyogianya diskusi kini beralih tentang bagaimana proses pembunuhan massal 1965 itu terjadi dan mengapa sampai memakan korban demikian banyak. Jadi, yang patut dipertanyakan bukan lagi “siapa dalang G30S” melainkan “siapa dalang pembantaian 1965″.
Buku Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto telah berhasil menampilkan data baru (berbagai dokumen dari dalam dan luar negeri), metodologi baru (dengan mengikutsertakan sejarah lisan) dan perspektif baru (ini adalah aksi bukan gerakan, tetapi kemudian dijadikan dalih untuk peristiwa berikutnya yang lebih dahsyat).
http://1r1yn.wordpress.com/